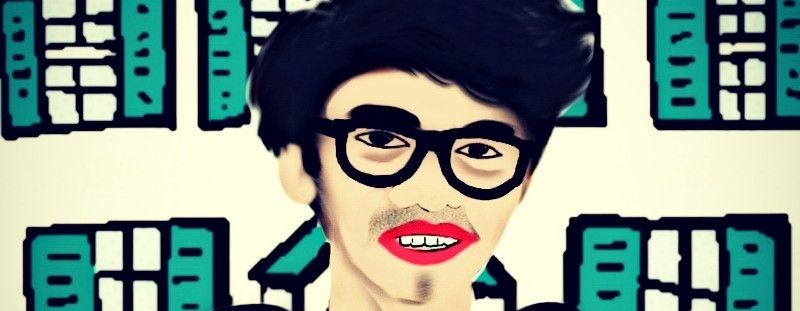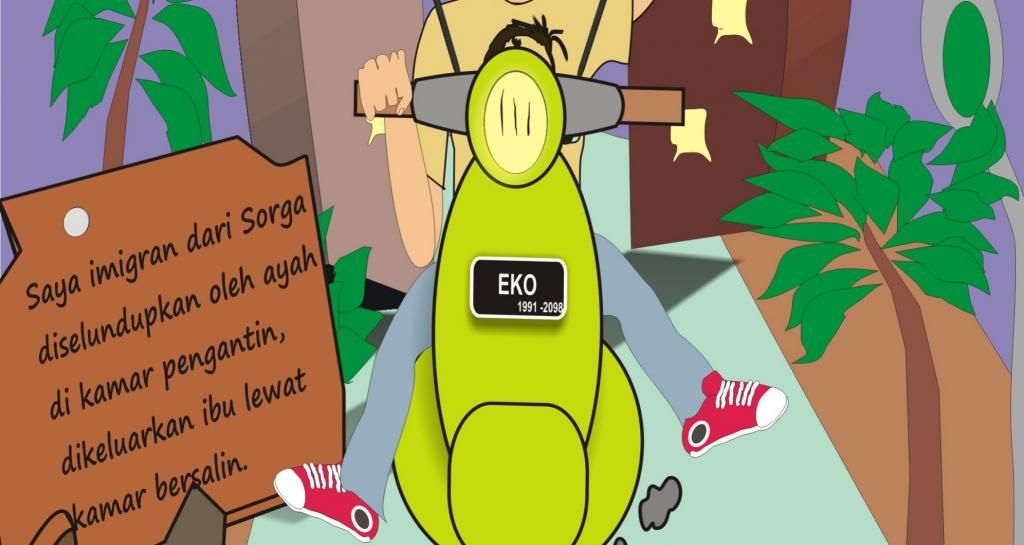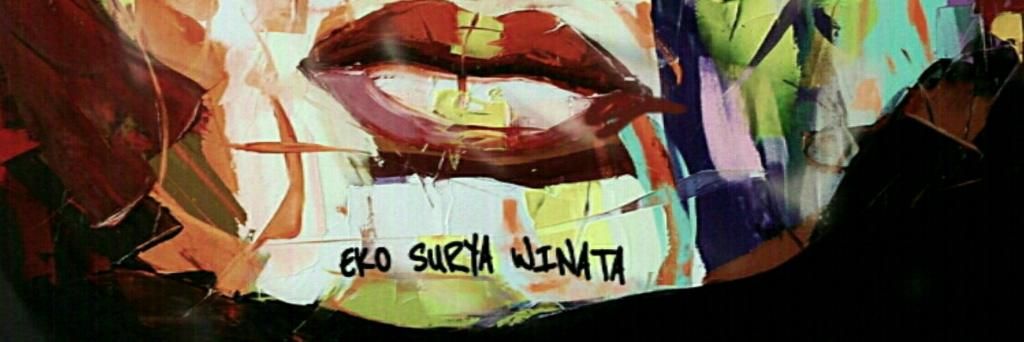Modernitas ditandai oleh proses rasionalisasi masyarakat dimana mereka mengganti pembicaraan tentang mitos dengan logos. Oleh karena itu muncul ilmu pengetahuan alam yang semakin maju sehingga menggeser struktur masyarakat yang primitif. Modernitas percaya bahwa sejarah bersifat progresif dimana masyarakat akan meninggalkan hal yang irasional. Hal ini berkaitan dengan konsep subjek modern yang dilandaskan pada etika promethean dimana manusia dipandang sebagai makhluk yang tunduk pada alam, sehingga manusia mengalami perubahan dari dalam dirinya dan lingkungannya.
Mengikuti perkembangan jaman, semakin lama banyak orang skeptis dengan konsep modern, khususnya yang diajukan oleh Liberalisme dan Marxisme. Kaum komunitarian menolak konsep tentang progresivitas sejarah yang dianggap sebagai ilusi, karena sejarah menciptakan alur yang tidak timbal balik (irreversibel) sehingga melenyapkan kosakata moral yang juga menjadi bagian di dalam masyarakat. Oleh karena itu konsep promethean dikritik karena memosisikan diri sebagai tuan, sedangkan yang lain sebagai budak.
Subjek promethean bukan cerminan dari suatu komunitas yang terkonstitusi di dalamnya tetapi menyalahi pemahaman tentang subjek. Subjek promethean menekankan pada diri secara atomistik sehingga mengabaikan yang lain (the other). Subjek tersebut cenderung menguasai alam, sehingga tidak menghormati subjek lain yang hidup dengan alam. Subjek promethean menggunakan logika instrumental dan gagal memahami subjek lain (the other) yang menggunakan logika non-instrumental. Homogenitas kemanusiaan ini menghancurkan yang lain, yang subjektivitasnya tidak berjarak dengan alam dan menolak rasio instrumental.
The other yang berlawanan dengan subjek promethean ini salah satunya adalah perempuan. Subjek promethean yang mengagungkan diri hanya ditujukan bagi masyarakat modern yang laki-laki tetapi tidak bagi perempuan. Perempuan tetap dianggap inferior, dan tidak dapat mengakses kemanusiaan yang utuh. Ketiadaan anggapan kemanusiaan yang utuh menyebabkan perempuan berada pada posisi yang subordinat dibanding laki-laki. Hal ini menyebabkan perempuan tidak dapat mengakses hak akan pendidikan, poitik dan ekonomi yang setara.
Boys Don’t Cry adalah salah satu film yang cukup merepresentasikan perempuan dalam masyarakat seaungguhnya masih menjadi subordinat. Film karya Kimberly Pierce ini diangkat dari kisah nyata seorang transgender bernama Teena Brandon yang dibunuh pada Desember 1993 di Nebraska, Amerika Serikat. Dalam film tersebut Teena menjalani pilihan yang sangat berat dalam hidupnya, yaitu menjadi transgender di dalam lingkungan yang kuat keyakinannya akan misogyny. Perilakunya yang memacari wanita awam (tidak tahu bahwa dirinya lelaki), membuat jengkel masyarakat di lingkungan rumahnya, hingga akhirnya Teena pergi dan bertemu dengan Lana (wanita yang dicintainya). Lingkungan dimana Lana tinggal sangatlah kental terhadap ego maskulinitas, hingga akhirnya Teena mengalami pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh dua lelaki kulit putih, yang tak lain adalah kerabat Lana dan Teena sendiri.
Mary Wolstonecraft menganggap bahwa perempuan didomestikasi sehingga tidak mampu mengembangkan kapasitas nalarnya. Meskipun Wolstonecraft tidak menggunakan kata peran gender yang dikonstruksi namun penilaiannya jelas mengandaikan bahwa terdapat peran gender yang tidak seimbang. Dalam pemerintahan ataupun dunia luar, perempuan dianggap lebih inferior daripada laki-laki. Apa yang membuat laki-laki dipandang lebih mulia adalah rasionya, sehingga kesempurnaan alam dan kapabilitas kebahagiaan perempuan, harus dikaitkan dengan rasio, kebaikan dan pengetahuan. Ketiganya menjadi derajat kemuliaan yang dimiliki laki-laki sebagai legitimasi masyarakat.
Dalam pandangan Women, Environment, and Development (WED) harus ada penolakan bagi perempuan terhadap pemberdayaan, yang bilamana tidak terdapat pemisahan antara laki-laki, perempuan, dan alam (Nature) di dalam rezim patriarki. Dengan demikian jelas penentangan terhadap konsep promothean. Heterosexisme dan ego maskulinitas adalah dua pilar yang selalu menjadi lawan emansipasi. Heterosexisme adalah suatu strategi ekonomi, politik, dan emosi praktis dalam melindungi konsep “pria” dan “wanita” (Feigenbaum, 2007; Hoagland, 2007). Cornell (2007) juga megatakan bahwa manusia seringkali berada dalam bayang heterosexual dikarenakan ketersesatan dalam memahami rasa takut akan dekandensi cinta. Cinta di sini adalah konsep yang diajukan untuk memahami identitas gender. Seharusnya dengan cinta yang ada kita akan lebih mudah dalam menjalin relasi sosial dan persahabatan dengan orang lain. Pengingkaran keberadaan LGBT (Lesbian, Gay, Bisex, Transgender) dalam masyarakat aalah suatu bentuk dehumanisasi yang halus sifatnya. Kerap kali pelecehan dan kekerasan bahkan menyertai ketidakberpihakan banyak orang terhadap eksistensi mereka.
Daftar Pustaka
Oetomo, D. 2003. Memberi Suara pada yang Bisu. Yogyakarta: Pustaka Marwa
Norton, R. 2002. A Critique of Social Constructionism and Postmodern Queer Theory: Queer Culture vs Homophobic Discourse. http://www.infopt.demon.co.uk/social24.htm. diunduh 2 Februrai 2010.
Mosse, Julia Cleves. 2002. Gender dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
Published with Blogger-droid v2.0.4