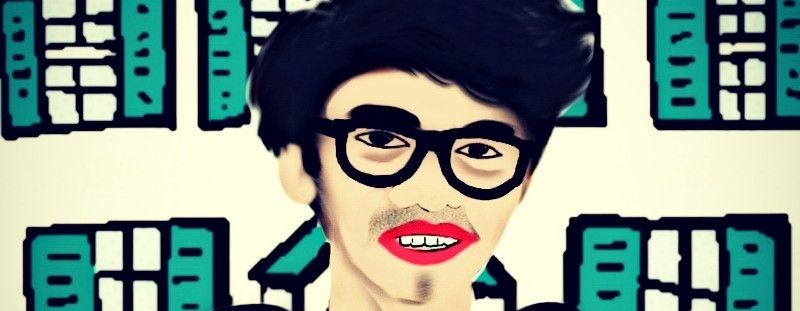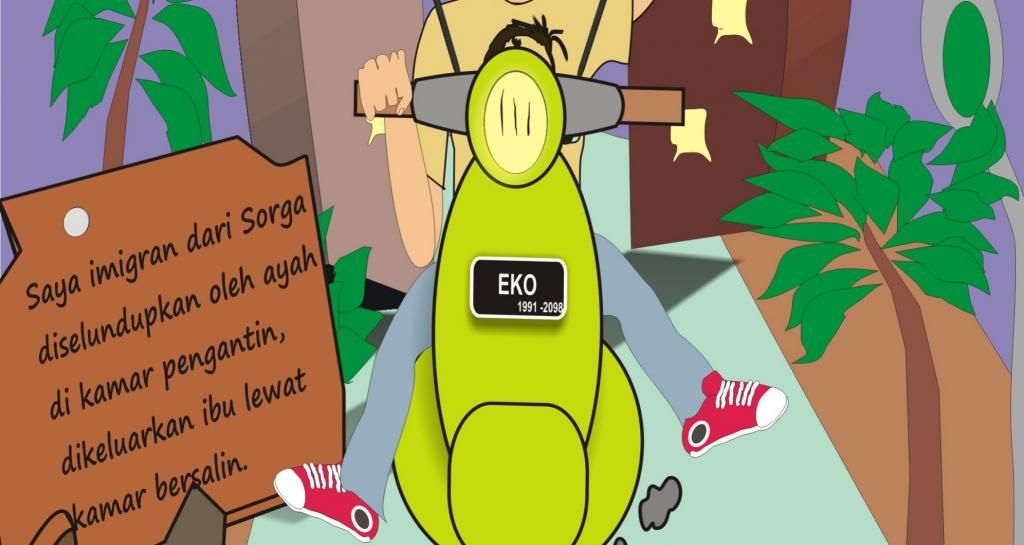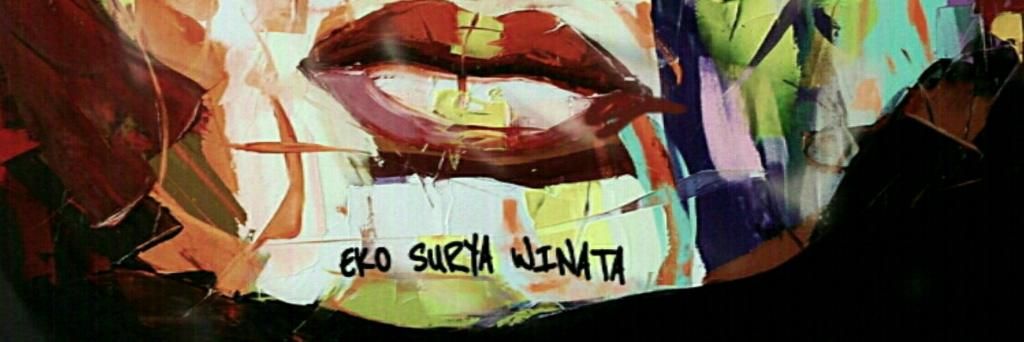Sabtu, 05 Mei 2018
KARMA: MISTISISME & MEDIA
Minggu, 28 April 2013
Dominasi Pemikiran Otak Kiri dalam Kognisi Barat
Plato dan Aristoteles waktu itu menghampiri kedai minumanku. “Wah kukira mereka sudah berdamai” Ujarku dalam hati. Gambaran itupun secara implisit berkeliaran di kepalaku, tepatnya bersamaan dengan nyanyian burung yang merdu seperti tak kenal bahasa makian.
“Bos, pesan es pocong dua!” Ujar Aristoteles yang matanya tak berhenti memandang sinis sang guru Plato. Aku sungguh takut, takut yang sebenarnya lebih disebabkan mimpi pocong semalam. Jujur sebenarnya aku sendiri belum pernah melihat materi yang disebut pocong. Tapi itu tak usah dibahas, lebih baik aku buatkan saja mereka es pocong, yaitu es sumsum campur kedelai, yang kupoles sedikit dengan seni (bukan air seni).
Memandang Aristoteles dan Plato, mengingatkanku pada pembedaan otak kiri dan otak kanan. Keduanya memang berlainan, dan memandang dunia dengan cara yang tidak sama. Otak kiri yang logis rasional, asertif, dan maskulin. Karakteristiknya memandang dunia secara linier, mengorganisasi input sensoris ke dalam bentuk titik pada suatu garis, secara berurutan. Yang aku tahu otak kiri lah yang menciptakan konsep kausalitas, yaitu kesan bahwa sesuatu menyebabkan sesuatu yang lainnya, karena ia selalu terjadi lebih dulu. Sebaliknya, otak kanan mampu memahami seluruh pola yang ada. Dia (otak kanan) adalah cenderung menerima segalanya dengan lebih bebas, feminis, resertif, mistik, dan intuitif. Aku memandang keduanya barangkali secara lebih kasar ialah, otak kiri ‘rasional’ dan otak kanan ‘irasional’.
Sembari aku memperhatikan Plato dan Aristoteles, aku masuk lagi ke dalam renung bawah sadar. Ya, benar adanya bahwa perkembangan ilmu pengetahuan menandai permulaan dominasi pemikiran otak kiri dalam kognisi barat dan menenggelamkan pertimbangan otak kanan ke dalam status ‘bawah tanah’ (bawah sadar) sehingga tidak pernah memunculkan apa-apa (yang diakui ilmu pengetahuan). Semoga di masa depan aku bertemu dengan sesorang yang menemukan ‘alam bawah sadar’ yang dia nyatakan sebagai alam gelap, misterius, dan irrasional (seperti halnya otak kiri memandang otak kanan). Sebagaimana Lao tse memahami fenomena yang sama ribuan tahun yang lalu (yin dan yang), meskipun mereka tidak pernah mengalami pembedahan pisah-otak.
Aku bermimpi mengajak manusia mengakui kembali aspek-aspek psikis yang lama dikesampingkan dalam masyarakat rasionalistik. Untuk dapat mengagumi dan menghargai sesuatu, orang harus memahaminya dengan cara khusus, meskipun pemahaman itu mungkin tak terdeskripsikan. Pengalaman ajaib-subjektif membawa pesan bagi pemikiran rasional bahwa objek keajaiban hanya dapat diamati dan dipahami dengan cara yang yang tidak sama dengan cara rasional.
"Apalah itu rindu, lebih baik kurasakan daripada harus kupikirkan" (Winata:69)
Minggu, 17 Februari 2013
Kita? Masyarakat? Negara? Nasi?
Kita dihidupkan di dalam masyarakat dimana tukang pizza datang lebih cepat ketimbang polisi. Dimana ketika kita melakukan sesuatu, kita juga harus melakukan sesuatu yang lain. Sama halnya seperti ketika kita buang air, kita juga harus membuang air yang lain. Ketika kecil banyak bicara dipuji-puji, saat sudah besar banyak bicara malah dimaki-maki. Dan uang sebagai alat pembayaran yang sah, memaksa kita untuk mencarinya, meski padahal kita tidak pernah merasa kehilangannya
Bumi ini memiliki air yang dari dulu volumenya tetap, tidak bertambah dan berkurang. Tapi bukan menjadi penyebab kita terbiasa membeli air untuk dibuang dan menjadi terbiasa salah menyikapi banjir. Kehidupan di bumi ini pun menyimpan banyak pertanyaan, seperti "Kenapa dinasaorus tidak ikut masuk ke dalam kapal nabi nuh, sehingga ia tidak punah karena banjir besar?"
Di tempat ini kita tumbuh besar, menjadi orang kuat. Saking kuatnya, kita hampir tidak pernah menangis, mungkin karena telah habis air mata. Acara-acara Televisi menjanjikan hiburan, agar masyarakat tidak stres menjalankan rumitnya modernisasi. Ternyata di sana ada sinetron yang belum juga tamat, karena ada banyak penonton yang menunggu tamat dengan cara terus mengikuti sinetron tersebut. Selain itu, di sana terdapat berita kecelakaan lalu lintas, kasus pembunuhan, korupsi pekerja negara. Adapun janji-janji calon wakil rakyat yang kelak suatu saat jika terpilih, mereka akan meminggirkan kita di jalan, baik macet ataupun tidak. Hahah.. Ada-ada saja, biasanya wakil tuh pengen naik jabatan, contoh wakil kepala sekolah ingin naik jadi kepala sekolah, wakil ketua kelas ingin naik jadi ketua kelas, tapi cuma wakil rakyat yang tidak ingin naik pangkat jadi rakyat. Ada juga acara-acara yang menyediakan tempat bagi seseorang yang ingin populer, di sana terdapat anak muda yang terlihat tua lebih lama dan orang tua yang ingin terlihat seperti anak muda. HAH! nampaknya ini hiburan yang mematikan, kepalaku ingin pecah melihatnya....
Tidakkah kau berpikir tempat ini adalah tanah airmu, namun tanah dan sawahmu digusur orang. Di sanalah kamu berdiri, tanpa sandang, pangan, dan papan. Sempatkah tersirat bahwa tempat ini juga adalah tumpah darahmu, namun kekayaanmu adalah juga milik negara. Kepadanya kau harus berbakti, apa kau pernah berpikir untuk pilih sibuk mencari nasi?
Selasa, 05 Februari 2013
Anekdot dari Niels Bohr
Siapa yang ga tau Niels Bohr? Fisikawan yang telah menggambarkan ke kita bahwa atom tersusun dari inti atom (nukleus) yang dikelilingi oleh orbit elektron. Bohr menerapkan konsep mekanika kuantum untuk model atom yang telah dikembangkan oleh Ernest Rutherford tersebut. Namun, aku ga akan membahas teori fisikanya, melainkan bercerita hal lain dari si Bohr.
Fisikawan kelahiran Denmark, 7 Oktober 1855 itu pernah mengeluarkan anekdot yang keren menurut saya (kalo ga keren jg gapapa sih). Oleh sebab itu, aku akan menceritakan anekdot tersebut. Semoga bermanfaat, bila tidak, maka manfaatkanlah. Jadi, begini kurang-lebih ankedotnya:
Suatu hari seorang anak perempuan (sebut saja Bunga), disuruh oleh ibunya.
Sang ibu berkata: "Bunga! Matikan televisinya!"
Bungapun menjawab: "Iya, bu" bergegas dia melaksanakan perintah ibu
Berteriak lagi ibunya: "Bunga! Cuci bajunya!"
"Baik, ibu" Sahut Bunga
"Beli sayuran sana kepasar!" Ibu memerintah beberapa waktu kemudian
"Siap ibu!" Bunga menyaut dan menjalankan perintah ibu
"Bunga!"
"Apa bu"
"Jangan jadi anak penurut!"
"Iya, baik bu"
Selasa, 29 Januari 2013
Cogito ala Derrida
Saya ga percaya dengan anjuran dokter syaraf. Katanya, selama sakit pendarahan otak kecil, saya harus istirahat berpikir. Sedikit tambahan tulisan untuk buku catatanku
Konsepsi tentang subjek ('aku') dalam sejarah filsafat modern sejak Rene Descartes (cogito ergo sum) bahwa subjek itu lengkap-bulat, ditolak derrida. Bagi Derrida konsepsi ala cogito ergo sum (aku berpikir maka aku ada) mengandaikan aku yang lepas dari relasi dengan unsur-unsur yang kendati mempengaruhinya. Bagi Derrida, aku cogito tak memiliki esensi metafisik, sempurna atau cukup bagi dirinya sendiri karenabia tumbuh oleh relasi bahasa Aku bagai modus semiosis Derrida muncul tak lengkap, nampak terpengaruh oleh psikoanalisis Jacques Lacan, aku dibentuk oleh teks-diskursus.
Terpengaruh konsepsi inter-subjektivitas oleh fenomenologi, Derrida menggantikannya dengan "intertekstual" yang mengandaikan terkuburnya subjek. Jelas karena 'aku' bentukan bahasa, bagi Derrida tak mungkin ada yg namanya individualisme, subjektivisme, humanisme, dll. Makanya, coba aja kalo Derrida main twitter dia pasti takjub dengan permainan bahasa twitter yg masing-masing akun punya ketrampilan khusus, itulah parole. Tapi Derrida tak menarik bahasa pada sisi struktur-lingguistik, bahasa baginya adalah diskursus, percakapan sebagai parole, wilayah pluralitas makna. Nah, kalo kita ketemu ada akun lain yg membetulkan/merevisi bahasa akun kita, optimisnya bagi Derrida pasti akun itu mau show off kekuasaannya. Tapi ketika ada power yg menyatukan semua akun harus menggunakan makna tunggal bahasa maka terciptalah langue, struktur, twitter berantakan.
Bersama pemikir post struktural; Foucault, Barthes, Lyotard, Baudrillard, Deleuze, yang tak yakin pada subjek cogito, mereka sabdakan manusia sudah mati. Karena 'aku' adalah bentukan teks dan teks itu adalah intensitas (menunjuk ke luar diri) maka jelas realitas sosial adalah sebuah 'jaringan tekstual'. Pada dimensi filsafat sebagai tindakan, pemikiran Derrida bersentuhan dengan filsafat bahasa Wittgenstein-2 dan filsafat performans John l Austin. Derrida dengan modus bahasa intertekstualnya membawa filsafat dari karakter refleksif/meditatif ke "modus tindakan". Bagi Derrida filsafat bukan bertugas mendefinisikan kebenaran dalam makna linguistik-logosentrisme, tapi menunjuk rangkaian tak ajeg. Derrida menarik filsafat dari angkasa ke sudut-sudut/marjin kasuistik, tiap kasus tak lepas dari kasus lainnya sebagai relasi semiosis. Dari konsepsi realitas semiosis inilah Derrida menolak hermenetika tentang subjek cogito yg menohok ke balik teks untuk temukan makna abadi. Tiap kasus atau pendefinisian bagi Derrida tidak hadir sebagai subjek penuh tapi bak perca yg lalu kita coba tempel dengan makna-makna yang mudah rapuh. Bagi Derrida menginterpretasi teks tidak untuk menemukan makna di balik teks itu, tapi bagaimana menangkapnya sebagai tanda-tanda untuk ciptakan makna baru.
Apakah Derrida anti atas hermenetika pencerahan yang demikian optimis dengan kekuatan subjek untuk temukan makna-kebenaran? Jawabannya ya, Derrida menolak optimisme hermenetika subjek dari Descartes sampe Husserl bahwa realitas seperti diadili di depan pikiran. Tiap teks adalah bentukan proses semiosis, rangkaian penanda yg infinit. Bagaimana mungkin kita mendekatinya dengan asumsi ada makna abadi di baliknya? Sejarah intepretasi merupakan pergumulan penanda yang hanya mampir sebentar di setiap halte - adakah terminal terakhir? Setiap interpretasi bagi Derrida adalah parole, karya yang tak bulat tp dengan begitulah dia justru kaya makna, yang bisa kita sebut sebagai 'kebudayaan'. Lalu di sinilah program dekonstruksi Derrida, berpikir adalah bertindak dgn mencipta makna baru atas ketidakhadiran penuh makna itu sendiri.
Senin, 01 Oktober 2012
Speculative Realism dan Quentin Meillasoux
Sejarah filsafat kontinental menunjukkan aliran realisme termarjinalkan, itu sebabkan 'Speculative Realism' bangkit melawan. Filsafat kontinental didasari pada paradigma: struktur pikiran dan bahasa, membuat realitas tersingkir. Paradigma struktur pikiran dan bahasa sudah muncul sejak Rene Descartes, Hume, Locke, Kant, Hegel, Husserl, Wittgenstein dan Derrida. Paradigma "Correlationism" menekankan 'Human-World Relation' tergantung pada pikiran dan bahasa. Cara pikir anti realisme disebut Quentin Meillassoux (pemuka speculative realism) sebagai paradigma "Correlationism".
Bagi Kant, pikiran hanya bisa mengetahui fenomena bukan noumena (inti) maka pengetahuan semata konstruksi pikiran atas apa yg ditangkapnya sendiri. Immanuel Kant meneguhkan dgn "Correlationism" inti realitas tak mungkin diketahui, dalam-dirinya- sendiri (Das Ding an Sigh). 'Very Strong Correlationism' Meillasoux pada thesis ini: noumena tak bisa diketahui dan dipikiran, itu tanpa makna, tapi bagaimanapun itu ada. Meillassoux membagi: Weak Corl, Strong, dan Very Strong Correlationism (Meillassoux sendiri berpegang pada yg terakhir). Bagi Kant, sekalipun inti realitas tdk bisa diketaui at least bisa dipikirkan, ini disebut Meillassoux sbg 'Weak Correlationism'. 'Anti Correlationism' Meillassoux tertuju pd kontruksi pikiran dan bahasa, sedang 'Correlationisme'-nya sendiri berdiri di atas matematika.
Sejarah filsafat kontinental sejak descartes dibangun pada 2 fondasi ekstrim: idealisme absolut dan realisme naif. Tujuan 'meillasoux' dengan Speculative Realism tak lain ingin mengatasi 2 ekstrim idealisme absolut dengan realisme naif Idealisme absolut, noumena tidak ada kecuali pikiran/idea itu sendiri, (realitas adalah idea). Realisme naif: noumena ada dan bisa diketahui. Bisa disebut sbg ;dogmatisme filosofis. Untuk mengatasi 2 ekstrim dalam sejarah filsafat itu, Meillassoux kemukakan konsep paradox: 'Necessity of Contigency', dari kategori Kant. Karena menolak bahasa dan kembali pd plato: filsafat sbg paradigma matematik, Meillassoux menggunakan matematik sebagai jiwa spekulatifnya. Apa yang real bagi meillassoux juga tidak sertamerta sesuai dengan ilmu-ilmu alam memperlakukan nature sbg yg real dengan hukum kausalitasnya. Alam bagi Meillassoux juga tak lepas dari konsep kontingensi, seolah-olah, tak berhenti pada prosedur hukum kausalitas. Matematika juga bersifat kontingen, tak terprosedurkan, Infinite. Jadi hanya kontingensi yg bersifat niscaya. (paradoks). Jika yang niscaya itu keseolahan itu sendiri samahalnya pikiran Meillassoux dgn filsuf Inggris Whitehead, yg pasti adalah ketidakpastian itu sendiri.
Pada Speculative Realism kita bisa membaca bahwa filsafat harus terus ke depan, memangkas Absolutisme dan Dogmatisme. Jika Matematika Spekulatif dipegang Meillassoux lalu bgmn hal itu bisa berhadapan dgn yang real?. Sayangnya seperti yg disintil temannya sendiri Graham Harman, Meillasoux tak bisa pisahkan matematika praktis dan spekulatif. Jika maksudnya matematika harus menspekulasikan realitas maka "Speculitve Realism" kembali pada modus "Dialektika Materialisme". Cara berpikir speculative realism tak memberikan radikalisme filosofis yang baru, pada semangatnya Anti Absolutisme/Dogmatisme jelas tidak. Pandangan Speculative Realism atas bahasa masih 'culun' belom paradigmatis, menjeneralisasikan bahasa semaunya. Jika pun Speculative Realism mau hidupkan lagi yg real, maka ia akan segera tenggelam ol prinsip Husserl "kembali pd benda itu sendiri" Banyak sekali pemikiran filsafat yang memberikan suntikan baru tapi tidak cukup membuat filsafat itu meradang-terjang.
Minggu, 23 September 2012
Harapan Ibu
Nak, saat ibu sudah tak mampu berdiri tegap. Tulang dan otot pun sudah tak mampu membantu berjalan lama, maka janganlah kau biarkan aku berjalan tanpa tongkat. Karena demikian aku 38 tahun yang lalu membantumu belajar berjalan.
Wahai anakku, tidaklah aku menuntut kesenanganmu. Akulah yang senang ketika kau senang, aku pun yang sedih saat dirimu sedih, dan aku yang malu saat dirimu bertindak memalukan, aku juga orangnya yg dengan tulus menyelipkan namamu pada tiap ucap doaku.
Dan janganlah kau merasa jijik saatku mulai malas mandi. Aku yg tak pernah letih memandikanmu sewaktu kecil, mengejarmu kesana-kemari.
Wahai anakku, janganlah kau membentakku ketika aku mulai menjadi pelupa dan tuli. Begitupun diriku saat dulu mengajakmu mengenal sesuatu, mengajarimu tentang suatu hal secara berulang-ulang.
Nak, janganlah kau berkata padaku dengan nada cemooh, saatku buta teknologi. Tiadalah letih diriku menghendaki dan mengenalkanmu ilmu pengetahuan dan teknologi sewaktu kau kecil.
Rawatlah diriku baik-baik saatku sakit, karena aku tidak mau tidak disampingmu saat kau juga demikian.
Temani diriku saat aku mulai tutup usia sayang. Aku tahu bukan usia yang menemukan arti kehidupan.
*Ibumu
Rabu, 13 Juni 2012
ANALISIS REVIEW FILM BOYS DON’T CRY
Modernitas ditandai oleh proses rasionalisasi masyarakat dimana mereka mengganti pembicaraan tentang mitos dengan logos. Oleh karena itu muncul ilmu pengetahuan alam yang semakin maju sehingga menggeser struktur masyarakat yang primitif. Modernitas percaya bahwa sejarah bersifat progresif dimana masyarakat akan meninggalkan hal yang irasional. Hal ini berkaitan dengan konsep subjek modern yang dilandaskan pada etika promethean dimana manusia dipandang sebagai makhluk yang tunduk pada alam, sehingga manusia mengalami perubahan dari dalam dirinya dan lingkungannya.
Mengikuti perkembangan jaman, semakin lama banyak orang skeptis dengan konsep modern, khususnya yang diajukan oleh Liberalisme dan Marxisme. Kaum komunitarian menolak konsep tentang progresivitas sejarah yang dianggap sebagai ilusi, karena sejarah menciptakan alur yang tidak timbal balik (irreversibel) sehingga melenyapkan kosakata moral yang juga menjadi bagian di dalam masyarakat. Oleh karena itu konsep promethean dikritik karena memosisikan diri sebagai tuan, sedangkan yang lain sebagai budak.
Subjek promethean bukan cerminan dari suatu komunitas yang terkonstitusi di dalamnya tetapi menyalahi pemahaman tentang subjek. Subjek promethean menekankan pada diri secara atomistik sehingga mengabaikan yang lain (the other). Subjek tersebut cenderung menguasai alam, sehingga tidak menghormati subjek lain yang hidup dengan alam. Subjek promethean menggunakan logika instrumental dan gagal memahami subjek lain (the other) yang menggunakan logika non-instrumental. Homogenitas kemanusiaan ini menghancurkan yang lain, yang subjektivitasnya tidak berjarak dengan alam dan menolak rasio instrumental.
The other yang berlawanan dengan subjek promethean ini salah satunya adalah perempuan. Subjek promethean yang mengagungkan diri hanya ditujukan bagi masyarakat modern yang laki-laki tetapi tidak bagi perempuan. Perempuan tetap dianggap inferior, dan tidak dapat mengakses kemanusiaan yang utuh. Ketiadaan anggapan kemanusiaan yang utuh menyebabkan perempuan berada pada posisi yang subordinat dibanding laki-laki. Hal ini menyebabkan perempuan tidak dapat mengakses hak akan pendidikan, poitik dan ekonomi yang setara.
Boys Don’t Cry adalah salah satu film yang cukup merepresentasikan perempuan dalam masyarakat seaungguhnya masih menjadi subordinat. Film karya Kimberly Pierce ini diangkat dari kisah nyata seorang transgender bernama Teena Brandon yang dibunuh pada Desember 1993 di Nebraska, Amerika Serikat. Dalam film tersebut Teena menjalani pilihan yang sangat berat dalam hidupnya, yaitu menjadi transgender di dalam lingkungan yang kuat keyakinannya akan misogyny. Perilakunya yang memacari wanita awam (tidak tahu bahwa dirinya lelaki), membuat jengkel masyarakat di lingkungan rumahnya, hingga akhirnya Teena pergi dan bertemu dengan Lana (wanita yang dicintainya). Lingkungan dimana Lana tinggal sangatlah kental terhadap ego maskulinitas, hingga akhirnya Teena mengalami pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh dua lelaki kulit putih, yang tak lain adalah kerabat Lana dan Teena sendiri.
Mary Wolstonecraft menganggap bahwa perempuan didomestikasi sehingga tidak mampu mengembangkan kapasitas nalarnya. Meskipun Wolstonecraft tidak menggunakan kata peran gender yang dikonstruksi namun penilaiannya jelas mengandaikan bahwa terdapat peran gender yang tidak seimbang. Dalam pemerintahan ataupun dunia luar, perempuan dianggap lebih inferior daripada laki-laki. Apa yang membuat laki-laki dipandang lebih mulia adalah rasionya, sehingga kesempurnaan alam dan kapabilitas kebahagiaan perempuan, harus dikaitkan dengan rasio, kebaikan dan pengetahuan. Ketiganya menjadi derajat kemuliaan yang dimiliki laki-laki sebagai legitimasi masyarakat.
Dalam pandangan Women, Environment, and Development (WED) harus ada penolakan bagi perempuan terhadap pemberdayaan, yang bilamana tidak terdapat pemisahan antara laki-laki, perempuan, dan alam (Nature) di dalam rezim patriarki. Dengan demikian jelas penentangan terhadap konsep promothean. Heterosexisme dan ego maskulinitas adalah dua pilar yang selalu menjadi lawan emansipasi. Heterosexisme adalah suatu strategi ekonomi, politik, dan emosi praktis dalam melindungi konsep “pria” dan “wanita” (Feigenbaum, 2007; Hoagland, 2007). Cornell (2007) juga megatakan bahwa manusia seringkali berada dalam bayang heterosexual dikarenakan ketersesatan dalam memahami rasa takut akan dekandensi cinta. Cinta di sini adalah konsep yang diajukan untuk memahami identitas gender. Seharusnya dengan cinta yang ada kita akan lebih mudah dalam menjalin relasi sosial dan persahabatan dengan orang lain. Pengingkaran keberadaan LGBT (Lesbian, Gay, Bisex, Transgender) dalam masyarakat aalah suatu bentuk dehumanisasi yang halus sifatnya. Kerap kali pelecehan dan kekerasan bahkan menyertai ketidakberpihakan banyak orang terhadap eksistensi mereka.
Daftar Pustaka
Oetomo, D. 2003. Memberi Suara pada yang Bisu. Yogyakarta: Pustaka Marwa
Norton, R. 2002. A Critique of Social Constructionism and Postmodern Queer Theory: Queer Culture vs Homophobic Discourse. http://www.infopt.demon.co.uk/social24.htm. diunduh 2 Februrai 2010.
Mosse, Julia Cleves. 2002. Gender dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
Selasa, 22 Mei 2012
Lady Gaga dan Filsafat Moral: Plato dan Marx
Dalam filsafat moral, tubuh dianggap sumber bencana (kerusakan moral) bukan pikiran, itu warisan filsafat Plato. Plato optimis pikiran adalah sebuah potensi untuk berabstraksi menuju dunia ideal (universally) tubuh menyerap dan menampilkan hal-hal yang menyesatkan. Jadi, segala kegiatan tubuh atau indra dianggap sepele oleh plato. Oleh karena itu jangan menari di depannya, apalagi sampai meliuk-liuk seperti Lady Gaga. Bila mengikuti moral plato, "aku" adalah aku-tubuh dan aku-pikiran yang jalannya berbeda (musuhan), dan kerja pikiran adalah mendisiplinkan tubuh. Tubuh hanya mengajak aku untuk bersenang-senang, nikmati hidup senikmat-nikmatnya, sehingga bagi Plato itu sangat banal. Aku nikmat (minum, makan, seks, begitu saja terus) hidup tanpa tujuan untuk sesuatu yg ideal, bagi plato merupakam hidup yang tak layak dihidupi. Jadi bila dilihat dari moral plato yg idealis, moral yg sangat metafisis itu, geliat-geliat tubuh Inul, Lady Gaga, Jacko, dll. itu cetek-banal.
Karl marx menyerang moral metafisis warisan plato yang dia sebut sebagai moral borjuasi. Menurutnya moral harus diturunkan ke bumi, bukan ke angkasa. Nietzsche-pun tak mau ketinggalan menyerang filsafat moral plato. Menurutnya bukan pikiran-idea (metafisis) letak permasalahannya, melainkan adalah kehendak berkuasa! (will to power). Bagi Marx moral merupakam kesadaran kelas proletar untuk merevolusi moral borjuasi platonik, seni misalnya bkn utk "dunia ideal" melainkan urusan 'perut'. Bagi kacamata marxian, nyanyian dan tarian Lady Gaga tak bisa diterima sejauh itu merupakam konstruksi borjuasi-kapitalisme! Kalo nyanyian-tarian lady gaga misalnya ternyta mudah diterima dan membangun kesadaran kelas proletar melawan kapitalisme, bagi marxis, Why Not?
Adendum:
Lady Gaga memang merupakan ikon budaya pop global, yang dikonstruksi oleh kapitalisme global. Bila tidak suka silahkan ambil gaya anti- neoimperialisme. Namun jangan hanya menolak lady gaga, tolak internet, handphone, dll, karena itu juga produk kapitalisme. Jika menjadi anti-neoimperalisme (kapitalisme global) yg taat, menolak lady gaga dan marah-marah di twiter/Facebook/email, dll. itu sangat menggelikkan. Namun jika menjadi anti-neoimperealisme yg setengah-tengah tidak sedikit munafik, yaitu menolak Lady Gaga tapi terima produk kapitalisme global lainnya. Dengan demikian kalo mau pakai ilmu gebuk musuh dgn ilmunya sendiri yah latihan dan kuasailah jurus-jurusnya, kuasailah kapitalisme dan jurus-jurus Lady Gaga! *eeaa
Minggu, 06 Mei 2012
Filsafat Ilmu: Sains dan Filsafat
Pengetahuan adalah makna/pembahasaan atas objek-objek abstrak atau kongkrit yang terjalin menjadi sebuah struktur pemikiran. Pengetahuan-bahasa-pemikiran, adalah tiga unsur yang tak bisa lepas satu sama lain sebagai proses mental dlm diri seseorang. Filsafat ilmu adalah kajian yang bersifat kritis, dan radikal tentang dasar, sumber, metode, validitas, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu berkaitan dengan: epistemologi, metodologi, sejarah ilmu, psikologi ilmu, dan sosiologi ilmu. Filsafat ilmu merupakan penyelidikan lanjutan (secondary reflection) terhadap ilmu pengetahuan. Manfaat filsafat ilmu, yaitu:
1. Memahami asumsi-asumsi atau dasar-dasar filsafat (ontologis, epistemologis dan aksiologis) ilmu pengetahuan;
2. Memahami bentuk-bentuk atau jenis-jenis ilmu pengetahuan, serta mengetahui kekuatan dan keterbatasannya;
3. Memahami ragam pandangan tentang dan penilaian kritis terhadap ilmu pengetahuan.
Filsafat membantu ilmu memikirkan dan menjawab apa yang tak dapat dipikirkan dan dijawab oleh sains. Sains menyediakan pertanyaan-pertanyaan bagi filsafat. Filsafat menyediakan konsep-konsep yang gejalanya dapat diteliti oleh sains. Ilmu pengetahuan modern menemukan banyak persoalan yang tak dapat dijawab langsung dengan metode-metode empirik. Perlu refleksi filosofis. Ilmu pengetahuan perlu menentukan asumsi-asumsi dasarnya yang pada dasarnya adalah filsafat tertentu.
Kurt Gödel: "Matematika sebagai logika sains memberikan bukti bagi keterbatasan sistem-sistem pengetahuan"
Sains berbeda dari cara perolehan pengetahuan lain karena penjelasannya. Motif sains adalah setepat dan sejelas mungkin menjelaskan gejala. Sedangkan flsafat ilmu menyediakan kerangka orientasi bagi ilmu untuk mendekati dan memandang gejala. Filsafat ilmu membantu ilmu untuk menyediakan kerangka pikir untuk menjelaskan, meramalkan dan mengendalikan gejala. Filsafat ilmu memikirkan dan mengkaji persoalan yang tak dapat dijawab oleh ilmu. Hasilnya: asumsi, kerangka pikir dan cara memahami ilmu.
Penjelasan ilmiah mengandung “explanans” atau “explanantia” = kalimat yang menjelaskan; dan “explanandum”atau “explananda” = kejadian yang dijelaskan. Ada filsuf yang mencari hubungan obyektif antara "explanandum" dan "explanans" sebab mereka percaya bahwa sains mengandung kebenaran tentang dunia. Ada juga yang percaya hubungan antara "explanandum" dan "explanans" adalah hasil konstruksi manusia dalam rangka memahami dunia. Filsuf yang mencari hubungan obyektif antara "explanandum" dan "explanans" menganggap penjelasan ilmiah mencerminkan kenyataan dunia . Flsuf yang percaya hubungan antara "explanandum" dan "explanans" adalah hasil konstruksi memandang penjelasan ilmiah sebagai alat manusia. Empirisme: pengetahuan dijustifikasi oleh pengalaman; kebenaran sains tak niscaya dan tak melampaui kenyataan yang ditemui dalam pengalaman. Rasionalisme: pengetahuan datang dari pikiran dan dijustifikasi oleh koherensi logis.
Ada yang beranggapan, penjelasan Ilmiah membutuhkan hukum-hukum yang mendasarinya, oleh sebab itu penjelasan adalah penjelasan sebab-akibat. Ilmuwan lain berusaha mengerti cara penalaran bekerja dalam penjelasan yang diberikan ilmuwan. Menurut mereka ilmu tak perlu mencari hukum. Awalnya ilmuwan mau menjelaskan obyek seharusnya. Tapi ini sulit sekali sebab observasi/eksperimen hanya menunjukan obyek sebagaimana adanya Ilmuwan belakangan tidak mencari hukum sebagai penjelas, melainkan lebih fokus pada bagaimana penjelasan menjawab pertanyaan orang. Ada dua pendekatan penjelasan ilmiah, yaitu:
1. Penjelasan sebab-akibat yang menyertakan hukum;
2. Hubungan sebab-akibat tanpa melibatkan hukum. Hubungan sebab-akibat yg tak libatkan hukum terdiri dari: 1. Unifikasi: memadukan berbagai penjelasan menjadi lebih lengkap, akurat dan umum; 2. Penjelasan teleologis: penjelasan beorientasi pada tujuan (telos);
3. Penjelasan dengan menekankan keniscayaan logis (logical necessity). Prinsip parsimoni berlaku: Penjelasan yang paling sederhana dan paling mungkin, serta paling luas jangkauannya yang paling diandalkan.
Antirealisme: memperlakukan teori sebagai sebuah alat heuristik (jalan-pintas), sebuah instrumen untuk meramalkan saja. Realisme: memandang teori ilmiah sebagai deskripsi yang bisa benar/salah dari fenomena yang teramati. Teori yang baik adalah teori yang benar.Realisme: berkeras bahwa hanya kesimpulan dari teori yang mendekati kebenaran yang dapat secara baik menjelaskan dan memprediksi gejala. Ilmu pengetahuan berikhtiar untuk merekonstruksi secara rasional alam yang ideal atau esensial yang hendak dijelaskan oleh teori ilmiah.
Equipped with his five senses, man explores the universe around him and calls the adventure Science. ~Edwin Powell Hubble (1954)
Every great advance in science has issued from a new audacity of imagination. ~John Dewey, "The Quest for Certainty", (1929)
Science increases our power in proportion as it lowers our pride. ~Claude Bernard
Kamis, 12 April 2012
Politik (Politea) Bukan Semata Tentang Kekuasaan Pragmatis
Politik adalah nama dalam filsafat untuk menandai penataan kehidupan bersama demi mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan yang hendak dicapai dengan politik adalah kebahagiaan yang dihasilkan dari memandangi kebenaran. Kini jarang ( mungkin tak ada) orientasi yang berkait dengan kebenaran. Tapi pernah ada politik yang bertujuan mencapai kebenaran. Pernah ada orang-orang yang berpolitik tanpa kepentingan selain kebenaran. Mereka berjuang menjalankan politik yang adil demi kebenaran.
Politik yang adil jadi soal penting bagi filsafat. Keadilan adalah pokok utama politik. Sebagai kajian filsafat, politik merupakan pikiran karena filsafat hanya berurusan dengan pikiran. Pikiran perpaduan tak terpisahkan antara teori dan praktik (praxis). Politik sebagai kajian filsafat bukan manajemen kepentingan atau usaha untuk mencapai kekuasaan. Bukan juga politik partai. Keadilan adalah nama dalam filsafat yang merujuk kepada kemungkinan kebenaran dari orientasi politik. Keadilan hanya bermakna dalam konteks politik.
Orientasi politik yang berurusan dengan kebenaran berciri umum: orang-orangnya melibatkan diri dengan syarat setia pada kemanusiaan generik politik yang bersentuhan dengan kebenaran memperjuangkan representasi kapasitas kolektif dengan patokan kesetaraan. Politik yang bersentuhan dengan kebenaran menjadikan kapasitas manusia sebagai patokan kesetaraan: manusia punya kapasitas untuk berpikir. Aksioma umum khas politik: Orang bisa berpikir; orang punya kapasitas kebenaran. Kesetaraan adalah maxim politik; sebuah preskripsi, aturan yg ditegakkan untuk mencapai pembebasan yang kolektif dari rezim di luar dirinya kesetaraan bukan program sosial, tidak bisa direncanakan. Bukan juga hasil distribusi ekonomi. Politik & keadilan tak terpisahkan. Keadilan adalah kata yang digunakan filsafat untuk mencapai aksioma egalitarian dalam kejadian politik.
Selasa, 03 April 2012
Hah, Eksistensialisme? Manusia Pusat Dunia?
Sedikit berkicau tentang eksistensialisme yang merupakan corak filsafat anti-kodrat dan menempatkan manusia sebagai pusat dunianya.
Eksistensialisme manusia dari keberadaannya bukan dari esensinya. Manusia kongkret dan ada di sana, di dunia.
Manusia terlempar di dunia: Keberadaannya di dunia bukan atas pilihannya. Setiap orang sudah menanggung keberadaannya sejak lahir (gen tertentu, keluarga, masyarakat, kondisi alam, dsb).
Paradoks keberadaan manusia: Keberadaan yang bukan pilihannya menjadi tanggung jawabnya. Manusia jatuh dalam masyarakat dan kehidupan sosial. Keberadaan manusia adalah keberadaan dalam dunia, bersama manusia lain. Dunia manusia adalah dunia bersama. Tiga jenis Dunia: Umwelt (dunia fisikal; alam), mitwelt (dunia bersama manusia lain) dan eigenwelt (dunia pribadi).
Setiap manusia adalah subjek: unik dan tak dapat diperbandingkan. Manusia tidak dapat dipahami dari esensinya. Manusia hanya dapat dipahami dari eksistensinya; dari keberadaannya di dunia bersama manusia lain.
Sartre: "Eksistensi mendahului esensi. Selama masih hidup, manusia tidak dapat didefinisikan karena masih berkembang dan belum jelas batasnya"
Jaspers: "Keberadaan manusia lain adalah penegasan kebebasan kita dan hubungan intersubjektif mungkin terjadi"
Sartre: "Neraka adalah orang lain. Keberadaan manusia lain adalah awal kejatuhan eksistensiku sebagai subjek"
Kierkeegard: "Tuhan adalah dasar dan penjamin eksistensi manusia; penjamin kebebasan"
Nietzsche: "Tuhan sudah mati. Manusia membunuhnya. Kematian tuhan menyebabkan manusia harus menentukan nilainya sendiri"
Nietzsche: "Untuk bisa menjadi pencipta, manusia harus jadi penghancur, juga menghancurkan tuhan sebagai nilai moral dasar"
Berdyaev: "Kebebasan tanpa syarat dan tanpa kompromi adalah kebebasan dalam Tuhan. Kebebasan baru bermakna jika dihadapkan pada imperatif (keharusan) di hadapan manusia-manusia lain yang juga bebas. Pandangan dunia manusia berbeda-beda; setiap orang memiliki pandangan dunia masing- masing yang unik. Esensi tidak dapat ditangkap; selalu terletak pada putusan subjek"
Kierkegaard: "Manusia pada dasarnya adalah pelaku (doer) bukan penahu (knower). Filsafat jangan instruktif, melainkan harus terlibat dalam kehidupan. Hidup bukanlah sebagaimana yang kita pikirkan, melainkan sebagaimana yang kita hayati. Manusia yang konkret dan nyata adalah yang individual dan subyektif. Manusia adalah pengambil keputusan dalam eksistensinya"
Nietzsche: "Rayakanlah hidup! Cintai takdirmu! Terima apa yang terjadi, juga penderitaan dan rasa sakit, sebagai hal baik. Hidup adalah apa yang kita lakukan hingga saatnya kita mati"
Sartre: "Tak ada kenyataan kecuali dalam tindakan. Manusia dikutuk untuk bebas; karena sekali ia terlempar ke dunia, ia bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya"
Eko Surya Winata: "Aku cinta kau itu urusanku, bagaimana kau padaku itu bukan urusanku"
Senin, 02 April 2012
Menolak Logosentrisme?
Dalam logos/langue mata intelek kita dikenai kacamata kuda agar mencapai kesimpulan atau rumus-rumus yg bermakna tunggal/ilmiah. Disiplin filsafat, ilmu maupun teologi saling berebutan posisi, mengklaim dirinya "kebenaran (tunggal)", makanya sikut-sikutan deh sampe skrg. Rumus atau kesimpulan ilmiah/filosofis yg bermakna tunggal itulah oleh filsuf Prancis, yaitu Derrida dinamakan "Logosentrisme". Logosentrisme pun membuat pikiran/mentalitas barat mendiskreditkan yg mereka bilang bukan barat, timur (tak punya logos = kebenaran).
Bahasa (logosentrisme) oleh Louis Althusser dilihat sebagai ideologi untuk jelaskan tentang cerita perjalanan kelas masyarakat. Dengan Althusser memasukkan bahasa ke dalam analisa sejarah sosial maka gerakan pemikiran kiri mulai membangun tradisi bahasa. Sama halnya pada kaum liberal, logosentrisme digunakan sebagai cerita tentang perjuangan kesadaran individual dan HAM. Baik kaum kiri maupun kanan sama-sama mengidap penyakit logosentrisme, klaim dirinya sebagai kebenaran tunggal/universalisme. Dengan istilah "logosentrisme" itulah Derrida menunjukkan penyakit arogansi pemikiran/filsafat barat!. "Logosentrisme" itu yg kemudian dibongkar oleh Derrida atau dgn istilah "dekonstruksi"!
Dekonstruksi melihat bahasa lebih pada makna perbedaan, jelas menolak hukum kacamata kuda yg melihat satu sama dengan kesamaan. Derrida menolak bahasa warisan aristotelian, pencipta logika, yg mencari makna/semantik sampai pada apa yg disebut "soul". Bagi Aristoteles makna bahasa bisa ditemukan pd ekspresi dari jiwa yg terwujud lewat kata-kata, yakni bahasa lisan. Menurut aristoteles bahasa lisan simbol dari jiwa, sementara bahasa tulisan simbol dari bahasa lisan, jd pentingnya bahasa pd lisannya. Sementara bagi Derrida bahasa lisan itu sebenarnya adalah bahasa tulisan, yg trlebih dulu menjejak di pikiran kita. Bagi Derrida tidak ada bahasa sebagai ekspresi murni, maka tidak ada subjek berbahasa (aku) yg bersifat metafisis sebgaimana pada Aristoteles itu. Ketika kita berbahasa seolah kita hadir langsung sebagai subjek pada teman atau lawan bicara, padahal tidak, ada makna yg tertunda dalam pembicaraan. Derrida mengedepankan perbedaan makna dari status kita berbahasa, jelas menolak logosentrisme. Dan memunculkan aliran poststrukturalis/postmodern.
" Dalam dunia makna jelas kita lepas dari konsep diri aku dan kamu sebagai dua yg berbeda dan saling mengobjek, relasi kita antar-subjek. Aku mengalami hidup bukan bagi dunia yang dideskripsikan namun dalam pengalaman2ku yg kuhayati sendiri scr eksistensial, kusadari sendiri" (Winata:69)
Selasa, 13 Maret 2012
Sekolah
Seorang pemuda telah datang ke rumahku. Dia adalah kawanku, seorang guru sekolah dasar di mana salah satu sepupuku sekolah di sana. Aku berkata kepadanya : “jika untuk bisa membaca dan menulis, tentu saja aku bisa mengajarkan dia di rumah. Jika untuk membuat dia menjadi banyak tahu akan ilmu, untuk itu tentu saja dia di rumah bisa membaca banyak buku dan aku ajarkan untuk menjelajah dunia maya”.
Guru sekolah itu bertanya: “Wahai engkau yang oleh dosen-dosenmu dipanggil siswa, sebab apakah sepupumu tetap engkau suruh untuk sekolah?”. Aku menjawab, yaitu setelah memakan kue: “Mereka harus bertemu manusia lainnya, untuk mendidik perasaan dirinya, bagaimana seharusnya dia bersikap atas adanya rasa benci selain cinta, untuk mendidik perasaan dirinya, bagaimana seharusnya dia membawa diri atas adanya rasa kecewa selain suka. Sebab setiap hal yang berhubungan dengan manusia, wahai engkau, akan selalu berkaitan dengan perasaan hatinya.”
“Untuk mendidik sehingga bisa memahami orang lain dan memahami dirinya sendiri agar kelak menjadi dirinya sendiri yang tahu diri dan berbudi luhur di dalam hidup bermasyarakat.” Guru sekolah itu tersenyum lalu berkata : “Kami dengar wahai engkau yang oleh dosen-dosenmu disebut siswa. Maka adakah hal lain yang ingin engkau sampaikan?”. Maka jawabku kepadanya : “Perbanyaklah waktu istirahat”.
Berkata juga aku kepadanya, seraya aku memijit punggungnya karena katanya dia sedang merasa pegal linu: “Dengarlah, Kawan, pada dasarnya semua orang sudah bisa baca tulis, tetapi adakah semua orang bisa membuat karya tulis? Pada dasarnya semua orang bisa mudah menekan gas dengan sekuat dia bisa, tetapi ketahuilah olehmu untuk bisa ngebut sangat dibutuhkan nyali.”
Berkata juga aku kepadanya: “Bagiku, maafkan jika aku salah, tetapi ruang kelas adalah bagai kurung untuk beo yang kau ajar bicara. Hendaknya ajaklah mereka pergi ke atas bukit, bertemu dengan dua bersaudara yang dianggap gila pada masanya yang justru oleh karenanya kita sekarang menikmati kapal terbang. Ajaklah ke kamar mandi, yaitu ke tempat di sana Archimedes mengutarakan Eureka atas hal yang telah dia dapatkan, yaitu apa yang selama ini dicarinya. Ajaklah pergi ke tempat berdebu karena Tagore adalah dia yang bicara kepada kita : “Anak-anak adalah mereka yang bersama debu”.
Dan juga berkata kepadanya : “Wahai, Kawan, tidakkah sampai kepadamu kabar, bahwa cabai kecil yang kita makan akan lebih terasa pedas daripada gambar satu bakul cabai di papan tulis?” Dia berkata: “Nah itu, bagian kiri dari punggungku rasanya pegal sekali”
Dan juga berkata kepadanya: “Wahai dikau yang oleh sepupuku dan kawan-kawan sebayanya dipanggil Guru. Pengetahuan rumus Einstein yang engkau berikan kepada murid-muridmu adalah rumus dari seorang Einstein yang berkata : ‘Imaginasi lebih utama daripada pengetahuan’”. Dia menjawab: “Kami dengar tentang itu, wahai Siswa.” Kataku kepadanya: “Mudah-mudahan bukan Cuma menjadi kata-kata hiasan yang engkau sampaikan kepada murid-muridmu.”
Dan juga berkata kepadanya: “Engkau sendiri sesungguhnya mengatakan kepada murid-muridmu bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik”. Maka, katanya kepadaku: “Demikianlah, kami hanya menjalankan kurikulum yang sudah diberikan oleh mereka”
Aku berkata: “Siapa pun mereka, maka katakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya bukan kurikulum yang harus selalu diubah, melainkan sikap dan pandangan masyarakat terhadap sekolah. Karena ketahuilah olehmu, bagi masyarakat, mereka menyekelohkan anaknya adalah untuk bisa mendapat ijazah, bukan ilmu.”
”Berharap ilmu sehingga tahu, berharap ijazah sehingga kerja, berharap kerja sehingga kaya, berharap kaya sehingga senang, berharap senang sehingga apa?”
Dan berkata kepadanya: ”Masihkah engkau berkata kepada murid-muridmu: ‘Jangan berpikir aneh-aneh, ikuti instruksi guru saja. Padahal, engkau tahu seorang genius adalah mereka yang dianggap aneh pada zamannya.”
Dan berkata kepadanya: “Sesungguhnya ini adalah hal yang membuatku bingung: manakala kita mengetahui bahwa perbedaan adalah sebuah rahmat, tapi mengapa justru kita menganjurkan murid-murid berseragam.” Dia tertawa dan katanya : “Aku tidak pernah memikirkan soal itu, Guru.”
Dan juga berkata kepadanya: “Tidakkah ini akan membuat engkau menjadi bingung sendiri? Guru PKN bilang bahwa semua agama itu benar, sedangkan guru agama bilang hanya satu agama yang benar?”
Dan berkata kepadanya: “Ketahuilah olehmu apa yang aku pikirkan tentang syair lagu ‘Taman yang paling indah adalah taman kanak-kanak’, syair lagu itu pasti bukan kalimat yang keluar dari hati nurani anak-anak TK, karena anak-anak tahu ada Dufan dan Walt Disney Park.” Dia berkata: “Benar, Siswa atau kau bisa kupanggil Guru.” Kataku kepadanya: “Jangan mengatakan benar hanya karena agar aku memijatmu.” Katanya: “Insya Allah tidak, Guru”
Dan berkata kepadanya: “Menuntut ilmu ke sekolah, tidaklah ini aneh bagimu? Karena kalau mau menuntut, seharusnya pergi ke kantor polisi. Menuntut ilmu ke sekolah malah akan dituntut balik oleh sekolah untuk membayar karena sudah menuntut ilmu di sekolah.” Dia memandangku dan tertawa, lalu berkata: “Guru pasti sedang bercanda soal ini.” Jawabku kepadanya: “Ya, engkau benar.” Lalu, aku lihat dia menangis, maka tanyaku kepadanya: “Mengapa engkau menangis?” Dia menjawab: “Agar menjadi dramatis, Guru”. Aku tersenyum dan menggeram: “HAHAHA….terima kasih”.
Senin, 12 Maret 2012
GALAU DAN EKSISTENSIALIS
“Galau adalah perasaan yang kau besar-besarkan untuk menguasai dirimu. Dia adalah wajar, begitu mempesona dan kau menginginkannya” (Winata: 69)
Galau itu gejolak pikiran dan pikiran itu penjamin eksistensi (ujung-ujungnya pilihan). Galau muncul karena kenyataan tak sesuai dengan yang diharapkan lalu jadi gelisah dibawa ke pikiran, nah mikir deh. Tapi pikiran juga jadi galau soalnya belum aja menemukan relasi yang oke antara hal-hal yang dipikirkan apalagi membayangkan suatu keputusan nanti. Kalo galau dibawa ke pikiran lalu mencoba tenang dan merangkai satu hal dengan lainnya, dapat titik temunya, nah itu asyik tuh jadi pemikiran.
Pointnya: galau itu sumber pengetahuan/ pemikiran, renungkan, dengan galau beranilah hadapi realita. Berat sih, ga sanggup? Paling larinya doa. Tapi kalo minjem kategori dari filsuf pencipta aliran filsafat eksistensialisme, Soren Kierkegaard, pemikiran galau itu masih tahapan dasar, estetik. Maksudnya bukan sekedar esteik = indah, tapi estetik = keindrawian. Galau estetik, sudah dalam pemikiran namun masih mudah tergoda oleh perubahan kongkrit (Inspirasi dari Kiekergaard). Galau-etis, pemikiran galau yang menyangkut dengan keputusan atau tindakan subjektif atas orang lain, menerima atau menyangkalnya. Galau-religius, nah ini baru kalau galau tak bisa dipecahkan oleh tahap estetik dan etis, lompatlah ke Tuhan (Inspirasi dari Kiekergaard).
Jadi tahap-tahapan galau itu, yang terinspirasi dari Kiekergaard: Manusia harus lebih dulu ngurusin soalnya sendiri, jangan langsung lompat pada Tuhan. Kiekergaard pernah kena galau-etis, sudah siap-siap nikah tau-tau batal seketika karena ketakutan kalo cintanya justeru tidak membebaskan. Itu persis Arthur Schopenhauer, tapi tak ada tahapan. Langsung ke “Die Leiden” (Nikmat itu Derita). Ya, Schopenhauer itu yang memperkenalkan galau dengan hashtag #nowplaying. Seni dan musik untuk kontemplasi kehendak pribadi. Schopenhauer itu galaunya kebangetan. Ngegabungin filsafat timur – Kant theorem dan Filsafat Weda – Upanishad.
Umumnya para eksistensialis galau-gagal dalam soal cinta (wanita)? Contoh Nietzsche, Kafka, Camus, Goethe. Nietzsche mau kawin dengan Lou Salome, tapi tidak diijinkan ibunya, ditambah sakit. Sartre punya kekasih meski hanya punya hubungan tanpa nikah dengan Simone Beauvior seperti Heidegger dan Hanna Arenth.
“Indahnya cinta tanpa perlu ikatan lembaga dan yang bisa dipertahankan bersama sampai liang kubur”. (Sartre)
"Cinta itu sejatinya hanya cukup untuk dirasakan. Bila kau menginginkannya itu sudah bukan cinta lagi, melainkan nafsu" (Winata:69)
Sabtu, 10 Maret 2012
Andai Nabi Adam Punya Ibu Mungkin Ia Tak Akan Nakal Makan Buah Khuldi
Kau mengajari aku mengucapkan kata-kata baru
Kaulah yang menghendaki aku mengucapkan kata-kata bagus
Kau adalah yang tidak membunuhku selagi masih bayi
Kau adalah yang tidak mengutukku hingga menjadi batu
Kau lebih tinggi dari aneka macam sorga
Kau lebih harum dari aneka wangi bunga
Kau adalah yang malu disaat diriku berbuat memalukan
Kau adalah yang lunglai disaat kutinggal pergi
Kau adalah yang tulus menyelipkan namaku pada tiap ucap doamu
Kau adalah yang menanyakan kabarku disaat ku tinggal jauh
Kau adalah yang berkata "Jangan Kecewa, Sabar Sayang"
Kau adalah yang kusebut namamu dengan getar kupanggil engkau "Ibu"
"Ibu, ketika engkau tersenyum padaku, cinta tak perlu lagi kucari darimu"
WAWANCARA IMAGINER ARISTOTELES
Aristoteles: “Hai Eko bangun.. sudah pagi, nanti keburu rejekinya dipatok ayam”
Eko : “Hah, oh iya om, gapapa saya bangun siang biar ayamnya matokin semua rejeki, jadi nanti ayamnya tinggal saya makan”
Aristoteles: “Hmmm.. Eko dengarlah”
Eko : “Kenapa?”
Aristoteles:: “Wahai Eko, mempelajari politik bagiku ialah mempelajari jiwa sebagai virtue and happines”
Eko : “Hah?”
Aristoteles: “By human virtue we maen not that of the body but that of the soul, and happiness also we call an activity of soul”
Eko : “ Apa itu maksudnya, om?”
Aristoteles: “Manusia muncul sebagai diri berkesadaran (subjek) berhadapan dengan dunianya sebagai kesatuan di luar dirinya (objektif). Sebelumnya manusia hadir sebagai bagian dari alam (kosmos) namun dengan kesadaran diri sebagai makhluk rasional, manusia hadir sebagai entitas mandiri. Manusia menjaga jarak dengan alam dengan pertanyaan mendasar apakah benda-benda atau kosmos? Siapakah manusia?”
Eko : “Mmmh.. terus?”
Aristoteles: “Dengan pertanyaan ini relasi mitis antara manusia dengan alam terputus. Alam sekarang dilihat sebagai kesatuan harmoni atau logos atau sistem. Manusia pun melihat dirinya sebagai makhluk rasional. Manusia dan alam sama-sama dianggap memiliki substansinya masing-masing namun punya perekat-rasionalitas.”
Eko : “Hmm.. terus korelasinya dengan statement tadi apa?”
Aristoteles: “Manusia tidak saja dilihat sebagai individu yang berpikir dalam menjadi manusia karena kehadiran manusia lainnya sebagai relasi sosial (polis). Maka yang menjadi fokus dari problem individu-sosial ini yakni bagaimana hakekat makhluk rasional ini mewujud dalam sosial?
Eko : “Hmmm.. (mikir)
Aristoteles: “Etika dan politik seperti satu koin dengan dua wajah dalam filsafat tentang nilai dariku. Apa yang menjadi tujuan dari tindakan manusia dalam hidup bermasyarakat bagiku ialah KEBAHAGIAAN.”
Eko : “Ohya, itu saya juga ga menolak”
Aristoteles: “Dengar Eko”
Eko : “Siap gerak”
Aristoteles: “Menurutku manusia ialah makhluk rasional, aku yakin tindakan manusia pun akan terarah dengan benar yakni pada kebahagiaan itu. Dengan hakikat manusia sebagai makhluk rasional, segala tindakannya pasti akan diperhitungkan demi sebuah tujuan. Yaitu tindakan bertujuan (teleologis)
Eko : “Maksudnya? Dia datang darimana om? Sok tahuku tak ada manusia egois yang mampu hidup dengan manusia egois lain,melainkan dirinya sendiri. Ketika kita berhadapan dengan manusia egois, bukankah kita juga menjadi egois, karena kita mengharapkan ia sesuai dengan kemauan kita.
Aristoteles: “Tindakan-tindakan yang membawa kita pada tujuan akhir yaitu kebahagiaan muncul dari jiwa (soul) yang mampu melihat kebaikan (good).
Eko : “Hmmm..”
Aristoteles: “Dalam jiwa kita mengenal adanya kehendak dorongan bagaimana tindakan untuk yang baik itu bisa mewujud pada masyarakat. Jiwa menunjukkan karakter seseorang bagaimana dia berinteraksi dan bertindak bagi kebaikan bersama tanpa kehilangan kediriannya yang rasional.”
Eko : “Berati apakah aku harus menyesal duduk di kursi kuliah jurusan politik?”
Aristoteles: “Kamu sudah besar, Rolling Stone bajumu. Engkau harusnya kecewa kenapa kau menyesal setelah tahu bahwa menyesal itu tidak berguna.”
Eko : “Iya”
Aristoteles: “Wahai Eko, hal yang baik muncul dari jiwa dan memungkinkan bangkitnya kebaikan bersama sebagai jiwa masyarakat . Kamu sudah benar belajar di politik, lakukanlah demi kebaikan bersama.”
Eko : “Oke banget. Om Aris”
Aristoteles: “Yang harus kau sedihkan adalah bila kau belajar untuk berhenti belajar. Berbahagialah”
Eko : “Siap boss”
Aristoteles: “Yasudah, salam ya buat keluarga”
Eko : “Iya nanti saya sampaikan, Eh iya om terima kasih ya”
*) Cerita ini diambil ketika saya tidur
Rabu, 07 Maret 2012
SUNYI
By: Eko Surya Winata
“Yang melingkupiku kini bukanlah keterkucilan, melainkan kesunyian yang indah. Pepohon di hutan ini pun bicara, bernyanyi, berpuisi; sopan, tak menggurui. Burung-burung berkicau menyuarakan kemerduan, bukan menyerapahkan makian. Rekah bebunga adalah kabar gembira tentang buah jerih payah yang bakal tiba. Tebing-tebing landai menyajikan damai. Reranting kuning merentang kenangan”
“Hai Winata, yang kau sering panggil itu diriku. Janganlah kau berharap puja untuk jaya dan lemah bilah dicaci. Karena sesungguhnya tidak ada yang suka dihina, termasuk aku; Tetapi keinginan untuk mendapat pujian sudah termasuk menghinakan dirinya. Dengarlah wahai diriku, setiap manusia akan melupakan apa yang dia mimpikan, apa yang dia harapkan, cita-citakan, yang dia permasalahkan, pada saat dia tidur; Karena sesungguhnya manusia hanya butuh tentram.”
“Oh inikah aku? Yang selalu bersama diriku dan selalu merasakan sunyi di malam harinya? Cobalah lihat semut di sampingku. Dia adalah yang berkata bahwa dirinya lebih hebat dari manusia. Dia tahu dengan keluar dari sarang dia akan terinjak, tergilas, terbunuh dan mati, namun demi mencari makan dia tetap membiarkan dirinya pergi keluar. Wahai Winata, hendaknya ajaklah diriku bertemu dengan seekor tikus, karena dia adalah yang tetap tinggal di tempat yang orang bilang kotor, menjijikan, jorok, hina; Namun ia tetap singgah di sana meski kita beri dia lantai yang berlapis emas. Dengarkan aku lagi wahai diriku yang mereka panggil kau itu aku, bila kau seekor kucing dan sekarang sedang tren menggong-gong; Maka janganlah kau ikut kursus menggong-gong, mungkin kau akan bisa, tapi apa kata orang bila melihat kucing yang menggong-gong. Winata, kita tahu bahwa laut itu indah, di sana terdapat banyak karang. Namun kita adalah ikan tawar, kita lebih memilih empang.”
“Duhai Winata, Hendaknya kau perlu berterima kasih pada matahari. Karena ia yang menyerap air di lautan, selokan, lubang-lubang di jalan, ingus di lubang hidungmu, dan air di mata hatimu. Lalu ia bersembunyi kala senja seakan tak harap puji. Dan langit di malam hari juga membawamu pada suatu kesadaran, bahwa ada benarnya teori relativitas Einstein; Bintang-bintang yang kau lihat sekarang barang kali adalah bintang yang sudah punah beribu tahun yang lalu, dan sinarnya baru sampai ke bumi; Sama halnya dengan mereka yang telah mendahului kita, mereka memang sudah tiada, tapi mereka masih ada di sini dalam karya, sensasi dan fantasi”
“Kau tahu bahwa sesungguhnya setiap manusia itu egois. Ketika kau beranggapan mereka egois, sesungguhnya kau juga egois, karena mengharapkan mereka sesuai dengan yang kau mau. Dengarlah Winata yang kucintai, sesungguhnya tidak ada manusia egois yang cocok dengan manusia lain melainkan dengan dirinya sendiri. Tetapi sunyi dalam kesendirian itu adalah keadaan yang tidak baik. Kau harus bertemu manusia lain, agar tahu bahwa kau tidak sendiri di bumi."
“Hai Winata yang aku meyakini hari terindah bagi ibumu adalah ketika kau dilahirkan ke bumi; Janganlah dirimu merasa malu, itu sudah menjadikan bukti bahwa kau ingin dinilai. Kau pun tahu, membuat orang lain senang adalah cara untuk membuat dirimu senang. Lakukan apapun untuk dirimu sendiri, bukan karena hal di luar dirimu. Aku mencintaimu, namun maaf aku lebih mencintai diriku”
“Kau puisi yang mustahil terwakili oleh diksi. Kata-kata lunglai di hadapan keelokanmu yang tak tepermanai. Bunyi bungkam citra pun buram, hanya kalbu sanggup bersitatap denganmu. Tak sehelai pun tali terlihat, tapi padamu aku terikat”
*) Lalu temanku telpon, mengingatkanku kalo besok ada kursus loncat indah jam 7 pagi.
Sabtu, 03 Maret 2012
Pengetahuan Adalah Sesuatu yang Disebar dan Berulang, Kebenaran adalah Suatu Hal yang Baru
Education is a social process. Education is growth. Education is, not a preparation for life; education is life itself. (John Dewey)
By : Eko Surya Winata
Pesona2 lama tentang kehebatan ras manusia, jenis kelamin atau fanatisme agama untuk merangsang nasionalisme mulai tidak manjur. Segala hal tentang siapa aku dan apakah baik atau buruk, berhasil atau tidak semuanya telah dipelajari sambil jalan. Ini cuma perjalanan dan kita bisa berubah semau kita. Karena permainan yang sebenarnya adalah mencari siapa diriku sebenarnya.
Sekolahku adalah alam semesta, disana aku bisa belajar semuanya dan semaunya. Pendidikan yang selama ini dibangun oleh kebudayaan kita, kebudayaan yang telah meminggirkan apa yang dianggap banal, chaotik, jelek, dan tidak baik adalah pendudukan atas generasi muda. Tak ada teori yang benar-benar sebagai sebuah kebenaran, setiap manusia memiliki teorinya sendiri untuk nyaman menjadi diri yang orisinil dalam berkarya.
Bila kau ingin bisa, maka belajarlah ilmu praktis. Tapi bila kau ingin mengerti, belajarlah filsafat (Anonimus). Bukan pendidikan, bila esensinya selalu bertentangan dengan esensi kreatifitas. Pandangan dunia manusia berbeda-beda; setiap orang punya pandangan dunia masing-masing yang unik. Dan segala hal yang kutemui itu sebenarnya ingin dikenal.
Sebagaimana Sokrates mengutip tulisan di Orakel Delphi: “Kenalilah Dirimu”. Tapi bagaimana? Diri tak menampilkan diri utuh dalam satuan waktu. Tak ada transparansi diri. Kita hanya mengenal diri lewat simbol. Diri kita bisa sangat akrab dengan kita, tapi di waktu lain bisa sangat asing. Apakah diri adalah satu kesatuan atau hanya kumpulan potongan-potongan pengalaman yang menghasilkan ilusi kesatuan? Apakah manusia memiliki pusat yang mengaturnya atau hanya fragmen-fragmen tingkah laku? Tapi menurut Kant: “Ego sebagai pusat diri dan otonom harus diandaikan ada. Jika tidak, tindakan manusia tak bermakna.
Dunia manusia adalah dunia serba kemungkinan. Manusia dapat memaknai apa yang nyata di depannya menjadi sesuatu ‘yang mungkin’ atau memilik kemugkinan makna lain. Menurut vitalilisme, manusia memiliki energi besar untuk berkembang lebih jauh lagi dari sekarang; lebih unggul lagi. Evolusi manusia tidak berhenti sampai manusia kini, manusia dapat berkembang lebih jauh lagi. Manusia memiliki energi hidup, elen vital, yang memungkinkannya membangun peradaban. Manusia mempunyai 3i; Instinc, intuition, dan intelegence. Intuisi mengandung kehendak bebas.
Pengetahuan adalah sesuatu yang disebarkan, sedangkan kebenaran adalah sesuatu yang baru. Kebenaran mengkonstitusi subyek, karena tak ada subyek tanpa kebenaran. Kebenaran, pertama-tama, adalah hal baru; sebuah proses yang berlangsung dalam kenyataan. Kebenaran awalnya adalah lubang dalam himpunan pengetahuan. Sesuatu yang tadinya tak diketahui, lalu dengan kesetiaan dibuktikan. Apa yang ada sekarang bukan dasar dari kebenaran. Tapi kesetiaan pada kebenaran dan ikhtiar menampilkannya dalam kenyataan jadi kriterianya. Di dunia selalu ada yang luput dari penandaan; sesuatu yang dianggap kosong; belum dipresentasikan. Kejadian kebenaran berasal dari situ. Setiap lubang yang tertutupi , celah yang terjembatani oleh kebenaran, membawa manusia pada pemahaman yang lebih lengkap. Tapi dunia tak terbatas, meski lebih lengkap dan lebih lengkap lagi kita memahami dunia, selalu ada yang luput. Kebenaran selalu terbuka.
ABSENSI BERDEBU MURIDKU DI TK VENUS BERACUN 03
Tayangan halaman minggu lalu
Mengenai Saya

- Winata Eko Surya
- Kunang-kunang, dulu aku kecil, kau-pun juga. Sekarang aku besar, tapi kau masih tetap saja kecil. Andai ada kunang-kunang sebesar diriku, maka akan teranglah dunia.